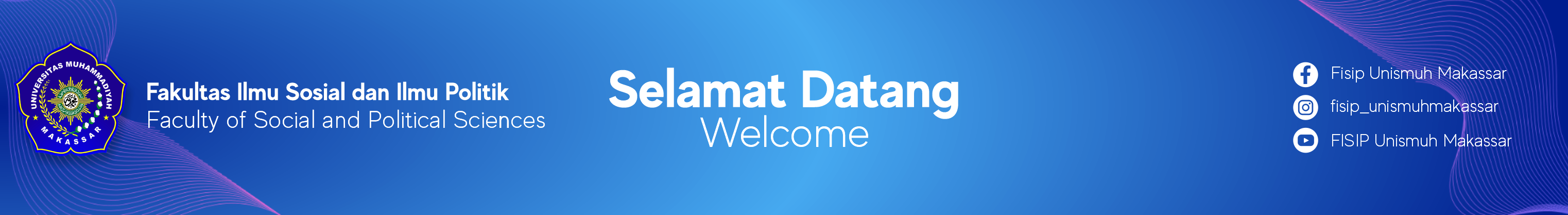Penulis: Abdul Gafur (Alumni Fisip Unismuh Makassar)
Dari pelajaran sejarah yang kini makin keras diingat: gedung-gedung bisa saja dibangun, bisnis maju, kota tampak indah, tapi si miskin tambah sengsara .
–Goenawan Muhammad
Menyusuri hutan-hutan jati
Melihat rumput-rumput yang terbakar di bawahnya
Menyaksikan sepur-sepur yang batuk membelah tanah Jawa
Arwah-arwah pekerja bergentayangan menuju ibu kota,
Mencipta banjir dari genangan air mata.
-Pramoedya Ananta Toer
“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.”
Demikian potongan kalimat Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR pada 16 agustus 2019 yang lalu, ini menandai babak baru pemindahan ibu kota Negara.
Wacana terkait pemindahan ibu kota Negara sudah diwacanakan sejak era orde lama, Bung Karno sebagai presiden pertama republic ini pernah menyampaikan keinginannya untuk memindahkan ibu kota Negara ke Palangka Raya itu diucapkan saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957.
Tidak sampai disitu, saat peralihan kekuasaan ke orde baru Presiden Suharto mengutarakan untuk memindahkan ibu kota Negara ke daerah Jonggol di Bogor.
Era Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden saat era reformasi juga menjadikan opsi pemindahan ibu kota Negara sebagai satu dari sekian opsi yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Kota Jakarta.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sepertinya tidak akan mewarisi presiden sebelumnya yang hanya menjadikan pemidahan ibu kota Negara sebagai wacana, setelah sempat tertunda karena bumi diserang oleh pandemic Covid-19, sepertinya presiden Jokowi tidak lagi tahan untuk segera mewujudkan ambisinya, pandemic yang memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan belum berakhir dan dalam tahap pemulihan dari berbagai aspek, melalui rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Puan Maharani mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi UU pada tanggal 18 januari 2022.
Pengesahan UU IKN ini menuai protes dari banyak kalangan, masa kerja yang hanya membutuhkan 40 hari kerja dan hanya mencakup 39 pasal dinilai tidak lazim, terkesan tertutup, terburu-buru sehingga dianggap mengabaikan mekanisme pembentukan perundang-undangan, sehingga dapat dianggap cacat secara procedural.
Secara subtansi pun demikian, berbagai persoalan masih menghantui penetapan dan proses pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang mencakup wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang nantinya wilayah yang masuk kawasan ibu kota Negara akan berganti nama menjadi Nusantara sebagai nama ibu kota yang diusulkan oleh Presiden Jokowi.
Sekalipun dalam berbagai dokumen disebutkan bahwa alasan pemindahan dan pemilihan tempat karena berbagai factor yakni, Resiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor, Lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia.
Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893km, terpendek kedua dari 5 calon ibu kota lainnya, Wilayah ini ada di dekat perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda, Insfratuktur yang relatih lengkap, dua tempat itu tersedia lahan yang sudah di kuasai pemerintah seluas 180 hektar.
Faktor –faktor tesebut bukan tanpa bantahan berbagai kajian dan penelitian serta fakta-fakta justeru nampak sebaliknya, peseoalan banjir sudah terjadi dikawasan sekitar wilayah persiapan ibu kota, aspek ekologis tentu akan paling berdampak, termasuk kawasan yang sebagian masuk wilayah konsensi tambang yang membuat kaget kepala Bappenas.
Pun pada akhirnya ibu kota Negara benar-benar pindah dengan konsep yang dibangga-banggakan pemerintah, semoga tidak mengikuti jejak proyek pembangunan Kota Meikarta yang mangkrak, aspek lain yang tetap penting untuk diperhatikan, seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai kelompok aktivis bahwa pemindahan Ibu Kota Negara juga dinilai sebagai agenda oligarki untuk mendekatkan pada pusat bisnisnya, serta bagian dari penghapusan dosa-dosa beberapa korporasi yang merusak di wilayah calon Ibu Kota Baru tersebut.
Bahkan kedepan bisa jadi bukan ibu kota Negara tapi menjadi ibu kota oligarki, Ibu Kota Negara tidak boleh menjadi tempat bersembunyi oligarki atau tempat perlindungan pejabat negara dari partisipasi public yang demokratis.
Pemindahan ibu kota Negara sebenarnya bukan sesuatu yang baru, banyak Negara yang pernah melakukan kebijakan tersebut, beberapa negara memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang, termasuk Rio de Jenerio ke Brasilia di Brasil yang dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam konsep yang ditawarkan mengacu pada apa yang terjadi di Brasil.
Dalam beberapa kasus banyak Negara yang dianggap sukses namun banyak pula Negara yang gagal dalam proses pemindahan ibu kota Negara.
Brasilia yang dijadikan rujukan bisa jadi sesuatu yang keliru, kegagalan Brasilia sebagai ibu kota karena hanya mengedepankan kemegahan arsitektur yang dianggap modern dan ikonik.
Sementara sebuah kota tidak boleh lepas dari identitas local, kehidupan manusia yang hidup didalamnya, perputaran ekonomi yang terjadi adalah populasi meningkat, gentrifikasi, harga tanah yang tidak terjangkau.
Gentrifikasi menjadi satu patologi social yang terjadi dihampir semua Negara yang melakukan perpindahan ibu kota Negara.
Lees dalam artikelnya mengatakan gentrifikasi sebagai konsep yang terus berkembang dan diperdebatkan hingga sekarang, gentrifikasi memiliki aneka macam pengertian, ahli perkotaan kontemporer yang bergelut dengan tema memberikan penjelasan yang fleksibel dan sederhana.
Gentrifikasi itu mengacu pada proses transformasi dari kawasan dengan kondisi fisik buruk dan kumuh atau juga lahan bisa kosong di perkotaan, menjadi aneka macam properti mewah yang hanya dapat dinikmati pekerja kerah putih atau “kelas menengah” atau properti lain untuk fungsi komersil.
Cita-cita untuk menciptakan kota modern melalui ibu kota Negara sebenarnya baik, jika konsep kota modern yang kita terapkan adalah kota yang inklusif dan partisipatif, tema perkotaan menjadi salah isu kontemporer yang terus dikampanyekan, pembangunan kota sebagai agenda politik menjadi penting karena jika tidak dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan ketimpangan hidup, ini menjadi masalah disemua kota-kota besar saat ini, apalagi PBB memprediksi tahun 2050, 70 persen dari populasi dunia akan tinggal di kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang intensif.
Kota yang dalam konteks ini adalah lokus kegiatan ekonomi dan kontrol politik dituntut memiliki model pembangunan yang demokratis dan ramah bagi semua penduduk atas dasar itulah kelompok masyarakat sipil terus mendorong right to the city sebagai komitmen bersama.
Terminologi Right to the City adalah slogan yang diartikulasikan oleh Lefebvre seorang sosiolog asal Prancis dalam masa-masa awal gerakan protes Mei 1968 terhadap pemerintah Prancis, tulisannya mengurai dampak negative dari system ekonomi kapitalis yang mengubah ruang-ruang perkotaan menjadi terkonstruksi hanya memenuhi kepentingan akumulasi kapitalis, tidak berhenti pada slogan, konsep Right to the City juga memperjuangkan usulan politis untuk perubahan dan sebagai alternative untuk kondisi perkotaan yang diciptakan oleh kebijakan oligarki yang menguasai elit pemerintahan.
Bagi Lefebvre, Right to the City berarti hak terhadap kota itu sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian, maka hak atas kota itu tidak sekadar dimaknai bahwa warga miskin berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, tapi juga warga miskin tersebut memiliki hak untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut.
Singkatnya, penduduk miskin yang menetap di kota tersebut bukan hanya pelaku pasif dari sebuah perubahan, tapi aktif terlibat dalam proses perubahan itu, dalam perkembangannya, gagasan “Right to the City” diterjemahkan oleh banyak gerakan sosial menjadi pilar-pilar yang merujuk pada usaha mencapai kota yang inklusif serta kualitas kehidupan urban yang memadai.
Harvey mengatakan Right to the City bukan sebuah inisiatif individu, lebih merupakan inisiatif dan kerja kolektif dari rakyat. Ini diakibatkan pembangunan kota yang neoliberalistik selama beberapa dekade terakhir.
Sugranyes dan Mathivet mencap right to the city itu perlambang dari sebuah perjuangan melawan neoliberalisme, sebuah perspektif politik baru melawan sebuah proses pembangunan perkotaan neoliberalisme, seperti privatisasi ruang perkotaan, komersialisasi penggunaan kota, mendominasinya kawasan-kawasan industri dan perdagangan.
Olehnya itu, right to the city mengandung dua aspek fundamental sekaligus yang tak terpisahkan: pertama, penolakan terhadap neoliberalisme; dan kedua, partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dalam proses pembangunan perkotaan.
Dalam upaya itulah, seharusnya proses perpindahan ibu kota Negara tidak hanya terfokus pada persiapan bangunan fisik yang megah dan “modern”, tetapi sejak awal mempersiapkan kota yang mengedapankan pendekat Right to the City sebagai bagian yang utuh dari perencanaan pembangunan ibu kota Negara tersebut.
Hal itu dimulai dengan pelibatan masyarakat adat/local dalam perumusan konsep ibu kota Negara yang baru dan mengadili perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kerusakan di wilayah tersebut, sehingga yang dikhawatirkan diawal ibu kota Negara Nusantara, bukan menjadi ibu kota Negara oligarki, tapi menjadi ibu kota Negara yang modern yang inklusif dan partisipatif sebagaimana prinsip Rigth to the City.
Kami sering mendengar kota-kota yang lenyap dari peradaban, runtuh tertimbun waktu. Semua itu terjadi bukan karena semata-mata seluruh bangunan kota itu hancur, tetapi lebih karena kota itu tak lagi hidup dalam jiwa penghuninya.
-Agus Noor
The cities of the world are concentric, isomorphic, synchronic.
Only one exists and you are always in the same one.
It’s the effect of their permanent revolution, their intense circulation,
their instantaneous magnetism
-Jean Baudrillard
Sumber: https://tekape.co/opini-ikn-nusantara-pengabaian-terhadap-konsep-right-to-the-city/